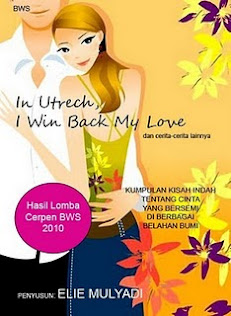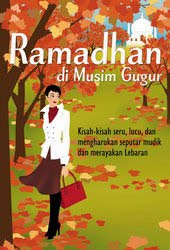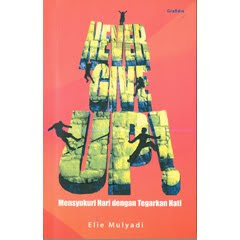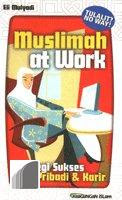Ramadhan di Musim Gugur
Jam dinding sudah menunjukkan pukul tujuh. Seharusnya mentari sudah muncul di langit, menyembul di antara awan-awan putih, menebarkan cahayanya yang semburat hangat. Tapi saat kusibakkan gorden jendela, ternyata hari masih gelap.
Aku bergegas mengenakan baju baruku. Gamis berenda warna hijau muda – senada dengan kerudung instan di kepalaku – yang baru sampai ke tanganku minggu lalu. Aku menyukai baju ini, baju yang dikirim oleh seseorang yang kucintai, seseorang yang selama hidup kupanggil dengan sebutan ‘Ummi’. Namun sayang cuaca dingin di luar membuatku terpaksa menutupinya dengan mantel tebal.
Setelah puas mematut diri, kulilitkan syal di leherku. Aku sudah siap berangkat sekarang. Namun tiba-tiba, jauh di lubuk hatiku, muncul semacam perasaan gundah. Ini hari lebaran, dan ini akan menjadi lebaran pertama yang kulewatkan jauh dari rumah. Aku rindu Ummi-ku, Abi-ku, dan adik-adikku yang berada jauh di negeri kelahiranku. Saat ini mereka mungkin sudah sholat Ied bersama di mesjid raya, kemudian berpelukan, bermaaf-maafan, dan saling merevisi arti kata ‘sayang’. Dan di sini, di cuaca pagi segelap ini, aku malah melangkah sendirian.
Bergegas aku menuju stasiun, mengejar kereta pukul delapan yang melaju dari Amsterdam ke Den Haag. Aku akan menuju suatu tempat di mana aku bisa menggenapkan ibadah puasaku selama bulan Ramadhan yang cukup melelahkan. Ya, tujuanku adalah Mesjid Al Hikmah, mesjid yang akan dikunjungi ratusan warga muslim Indonesia dari berbagai penjuru Belanda. Di sana aku akan menunaikan sholat Ied untuk yang pertama kalinya.
Duduk di kereta sendirian, di tengah orang-orang tak dikenal yang mungkin punya tujuan sama denganku, membuat dadaku terasa pilu. Baru dua bulan aku menginjakkan kaki di negeri kincir angin ini, demi menempuh studi masterku di Universiteit van Amsterdam melalui beasiswa. Dan kedatanganku langsung disambut oleh bulan yang suci ini, bulan yang ketika berada di tanah air selalu kunanti-nanti.
Aku masih ingat, minggu lalu umurku genap dua puluh tiga. Tapi Ramadhan pertamaku, di sebuah negeri asing, membuatku sering menangis seperti anak kecil. Bukan karena puasa di sini berlangsung dari waktu subuh sampai pukul delapan malam, alias dua jam lebih lama dibanding ketika puasa di negeri sendiri. Bukan pula karena selama tiga puluh hari berturut-turut aku harus mengosongkan perut di tengah cuaca dingin yang membuatmu terus menerus lapar dan ngantuk. Juga bukan karena aku menjadi kaum minoritas yang harus selalu siap menjawab pertanyaan dari teman-temanku sesama mahasiswa. Tentang kenapa aku berjilbab, kenapa aku sholat, kenapa aku puasa, dan kenapa-kenapa lain yang membuatku harus terus menerus menjelaskan identitas kemuslimanku.
Tapi karena aku sendirian. Ya, aku sendirian. Di bulan Ramadhan, dan sekarang, di hari Lebaran. Hari yang seharusnya kuhabiskan bersama keluarga, akan berlalu begitu saja tanpa perasaan istimewa.
Dulu, saat aku masih tinggal di rumah, Ramadhan selalu terasa indah. Ummi – ibuku- sibuk di dapur kesayangannya, membuat makanan lezat untuk kami sekeluarga berbuka. Ketika adzan maghrib tiba, aku dan adik-adikku berlarian ke meja makan, berebut tajil kurma dan kolak pisang. Tajil langsung diikuti dengan nasi hangat, sup ayam, goreng ikan, dan seabreg santapan lezat yang selalu terhidang di meja selama bulan puasa. Belum lagi kue-kue kering dan buah-buahan pencuci mulut. Segala yang ketika siang hari terlihat lezat dan membuat lapar, akhirnya tak muat semua di perut. Kami terkapar kekenyangan. Kemudian Abi – ayah kami – akan mematikan tayangan sinetron Ramadhan di televisi, membangunkan kami untuk berwudhu dan melaksanakan sholat berjamaah di mushola keluarga. Setelah itu kami bersama-sama menuju mesjid kompleks untuk sholat isya dan tarawih. Malamnya kami tadarus, lalu tidur dan dibangunkan untuk sahur.
Semua itu tak ada di sini. Meski banyak orang bilang aku gadis yang beruntung bisa kuliah di luar negeri, pada kenyataannya ‘berada di luar negeri’ tidaklah seindah kedengarannya. Terutama jika kau menghadapi hari raya. Kenyataan berada jauh dari rumah membuat hatiku nelangsa.
Aku rindu opor ayam dan ketupat buatan Ummi. Aku rindu suara takbir yang dilantunkan Abi. Aku rindu keributan yang dibuat oleh adik-adikku, saat mereka bangun pagi, berlarian ke kamar mandi, mengenakan baju baru, dan berlomba menjadi yang pertama duduk di mobil untuk menuju ke mesjid raya. Setelah sholat Ied dan salaman dengan semua sanak saudara dan tetangga, mereka berebut aneka hidangan lezat di meja. Ziarah ke makam keluarga dilakukan pada sore harinya. Semua itu rutinitas, yang pernah kujalani selama dua puluh dua kali dalam hidupku. Namun sekarang, aku malah merindukan rutinitas itu. Ya Tuhan, betapa aku ingin pulang!
Tak terasa kereta yang kutumpangi sudah tiba di Den Haag Centraal Station. Sesuai petunjuk yang telah kuperoleh sebelumnya, aku segera mencari Tram nomor 16 jurusan Moerwijk. Selama 20 menit lamanya aku duduk di kendaraan umum kota yang disesaki ratusan jamaah Idul Fitri ini. Untuk pertamakalinya sejak menginjakkan kaki di negeri asing ini, aku bertemu dengan ratusan orang berbahasa Indonesia, dari berbagai kalangan usia, yang mungkin juga bernasib sama. Tapi berbeda denganku, wajah-wajah mereka ceria, anak-anak berceloteh riang gembira, meski garis nasib telah membuat mereka terpisah jauh dari keluarga. Ah, mungkin karena mereka sudah lebih lama tinggal di Belanda, pikirku.
Ketika tram yang kutumpangi berhenti di halte Heeswijkplein, aku dan semua penumpang turun. Mesjid Al Hikmah sudah berdiri menjulang di hadapan. Bersama ratusan orang lainnya, aku berjalan menuju mesjid itu. Takbir dan takhmid sudah berkumandang menyambutku. Dan hatiku tergetar pilu. Kulihat di sisi kanan kiriku, pepohonan menggugurkan daun-daunnya. Sangat cocok dengan suasana hatiku yang kelabu.
Ketika sedang sibuk menghayati irama takbir yang menggetarkan hati, bersama rasa sendiri yang menyelimuti, tiba-tiba sesuatu menyentuh sarung tanganku. Tidak, bukan sarung tanganku, melainkan jemariku yang tertutup sarung tangan. Aku menoleh untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan di sanalah seseorang dalam balutan mantel kuning tengah menatapku, tersenyum padaku. Tidak, dia tidak hanya tersenyum, melainkan mengembangkan kedua tangannya untukku.
“Lestari, kamu masih ingat aku?” katanya sambil mempertontonkan matanya yang berbinar.
Aku diam tak bersuara, tak tahu harus melakukan apa. Oke, dia gadis berwajah Indonesia, memakai mantel yang mirip denganku, memakai kerudung sepertiku, dan usianya pastilah tak beda denganku. Tapi aku tidak mengenal gadis itu, dan namaku bukan Lestari. Mengapa dia bersikap seolah sedang tanpa sengaja menemukan sahabat lama?
Menyadari aku diam saja dalam kebingungan, gadis itu segera bertindak duluan. Dia memelukku. Beberapa saat lamanya dia memelukku erat, sehingga daun-daun musim gugur sempat jatuh di antara kepala kami. “Kau pasti tidak ingat aku, kita kan sudah lama nggak ketemu sejak lulus SMA.”
Sesaat terbersit di kepalaku untuk menyebutnya orang gila. Tapi sebuah seruan pengumuman dari masjid membuat kami segera melepas pelukan dan berlari untuk mengambil air wudhu. Jam sudah menunjukkan pukul 9.05, sholat ied akan segera dimulai. Sayang sekali mesjid ternyata sudah disesaki oleh antrean, dan ukurannya terlalu kecil untuk menampung semua jamaah. Karena pengurus tidak mengijinkan jamaah untuk sholat di luar mesjid seperti yang umum terjadi di Indonesia, akhirnya sholat Ied dibagi menjadi dua sesi. Aku yang datang agak terlambat, kebagian sesi kedua. Dan saat itulah aku punya kesempatan untuk membuka percakapan dengan gadis yang barusan memperlakukanku sebagai teman lama.
“Maaf, tapi namaku bukan Lestari, dan setahuku aku tidak punya teman SMA sepertimu,” kataku sambil memeluk mukena...
Penasaran dengan cerita ini? Temukan kelanjutannya beserta kisah-kisah indah dan inspiratif lainnya dalam buku terbaru yang akan beredar di seluruh toko buku Gramedia mulai tanggal 25 Agustus 2009 ini. Berikut deskripsinya:
Judul Buku: Ramadhan di Musim Gugur
Genre: Koleksi kisah inspirasi & pengembangan diri
Penulis: Elie Mulyadi dkk
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Harga: Rp 38.000,-
Tebal: 264 hlm
Rabu, 19 Agustus 2009
Langganan:
Postingan (Atom)